Disclaimer: Catatan pembelajaran ini tidak memberikan informasi spesifik berupa nama korban dan pelaku, alamat tempat tinggal korban maupun pendamping korban, dan informasi spesifik lainnya yang dapat mengancam keamanan korban. Informasi lebih lengkap hanya dijelaskan dalam dokumen laporan pendampingan. Catatan pembelajaran hanya memberikan informasi terkait kasus secara singkat, kondisi korban, bentuk kekerasan, faktor yang memengaruhi kondisi korban, proses dukungan psikososial dan pendampingan korban, strategi, tantangan dan refleksi dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh tim konselor dan pendamping korban dari Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya). Layanan dukungan psikososial dan pendampingan korban secara langsung selama April-September 2025 ini didukung oleh Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Pundi Perempuan 2025 Termin I.
Seorang perempuan merasa putus asa setelah lima tahun terperangkap dalam pernikahan penuh kekerasan. Dia merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran rumah tangga oleh suaminya sendiri, yang secara berulang melakukan kekerasan fisik, verbal, dan finansial, bahkan di hadapan anak-anak mereka. Di tengah rasa takut dan kebingungan yang terus menghantui, korban akhirnya memberanikan diri mengakses platform @perempuanberkisah dari Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh dan Berdaya (Pribudaya). Korban kini telah mengajukan gugatan cerai dan mengikuti dua kali persidangan. Namun, dalam proses tersebut, ia merasa dirugikan karena pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikannya diabaikan oleh hakim. Menjelang persidangan ketiga, korban akhirnya menghubungi pos bantuan hukum (posbakum) untuk meminta pendampingan dari advokat agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil.
Apa yang Terjadi pada Korban?
Berdasarkan pernyataan korban, korban mengalami KDRT secara fisik, verbal, dan finansial selama lima tahun pernikahan, serta mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh. Lebih menyakitkan lagi, kekerasan fisik itu kerap terjadi di hadapan anak-anak mereka. Setiap kepulangan pelaku ke rumah justru memunculkan rasa takut dan cemas dalam diri korban. Pelaku sering menyalahkan korban atas segala sesuatu yang terjadi dan melakukan gaslighting agar korban merasa bersalah dan tidak berdaya. Selama menikah, korban tidak pernah didengarkan dan selalu dianggap salah.
Di tengah situasi ini, korban akhirnya mengajukan gugatan cerai pada pertengahan 2025. Namun, sebelum sidang pertama, ia diliputi rasa ragu dan cemas apakah keputusannya tepat. Korban takut dianggap kurang sabar, takut akan karma, dan merasa berat meninggalkan rumah tangganya. Pihak keluarga pelaku bahkan berusaha untuk membujuk korban untuk berubah pikiran dan berusaha agar korban menangguhkan perceraian.
Manipulasi Pelaku dan Tekanan Hakim yang Tidak Berpihak
Setelah sidang pertama, pelaku masih sering menghubungi korban, tetapi komunikasi itu tidak pernah membawa kelegaan. Sebaliknya, pelaku terus menyudutkan korban atas keputusannya menggugat cerai, menganggap langkah itu sebagai bentuk ketidaksetiaan, dan kesalahan fatal. Pelaku bahkan beberapa kali menunjukkan sikap seolah merasa bersalah, tetapi dibalut dengan manipulasi emosional.
Dalam proses persidangan, tekanan yang dialami korban semakin berat. Hakim meminta ada mediasi kembali, meskipun korban telah tegas menyatakan tidak ingin rujuk. Pernyataan korban tidak dianggap serius oleh hakim dan justru dilakukan mediasi sekali lagi. Di depan publik, pelaku tampak meyakinkan dan terlihat seperti sosok yang layak dipercaya, sehingga banyak pihak memihak padanya.
Ketika sidang kedua berlangsung, tekanan datang tidak hanya dari pelaku tetapi juga dari pihak keluarga pelaku yang berusaha mendamaikan mereka. Hal ini mengakibatkan korban menghadapi banyak tantangan dalam proses hukum. Korban merasa suaranya tidak didengarkan dan kesaksiannya diabaikan. Korban berkali-kali menyatakan bahwa ia sudah tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan, tetapi hakim tampak lebih mengedepankan “perdamaian” semu daripada mendengarkan kebenaran dari korban.
Situasi ini menambah beban psikologis yang besar bagi korban, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keberpihakan dalam proses hukum. Karena merasa dirugikan dalam proses sebelumnya, menjelang sidang ketiga, korban akhirnya mengakses pos bantuan hukum (posbakum) untuk mendapatkan pendampingan advokat dan memperkuat posisinya dalam memperjuangkan haknya sebagai korban.
Proses Pendampingan Psikososial dari Tim Perempuan Berkisah
Setelah menerima informed consent, korban diarahkan oleh admin menuju ke Ruang Aman untuk melakukan konseling secara online.
1. Sesi Pendampingan Pertama
Dalam sesi pertama, korban menyampaikan kecemasan dan kebimbangan yang ia rasakan, terutama terkait keputusan menggugat cerai. Konselor melakukan psychological first aid (PFA) dan memvalidasi perasaan korban, termasuk keraguan dan ketakutannya. Konselor menjelaskan bahwa keputusan korban untuk bercerai sudah tepat karena KDRT tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Konselor juga membantu korban membedakan antara ujian pernikahan dan bentuk kekerasan yang sistematis. KDRT adalah bentuk ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku berupaya menekan dan memanipulasi korban sehingga korban kehilangan daya dan selalu merasa bersalah. Sebaliknya, ujian pernikahan adalah tantangan yang dihadapi bersama secara setara, bukan bentuk penindasan.
Dalam sesi pertama ini, korban juga menyampaikan kebutuhan untuk didampingi secara langsung. Setelah dilakukan pemetaan wilayah, diketahui bahwa korban tinggal di daerah yang sama dengan salah satu anggota komunitas Perempuan Berkisah (PB). Setelah pemetaan wilayah dan kebutuhan, konselor Yayasan Pribudaya membentuk grup daring untuk koordinasi antara konselor, pendamping lapangan, dan korban sebagai dukungan berkelanjutan.
2. Sesi Pendampingan Kedua dan Ketiga
Dalam pendampingan lapangan berikutnya, pendamping bertemu langsung dengan korban untuk memastikan kesiapan emosional dan administratif menghadapi proses persidangan. Saat sidang pertama berlangsung, anggota PB turut mendampingi di Pengadilan Agama di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Meski tidak diperkenankan masuk ruang sidang, kehadiran anggota PB di luar ruang berupaya memberikan rasa aman dan dukungan emosional bagi korban. Grup koordinasi juga menjadi ruang aman tempat korban membagikan perasaannya selama menjalani proses perceraian.
Refleksi Pendampingan Korban
Negara Lemah dalam Melindungi Korban KDRT
Pada kasus ini, korban sudah mengumpulkan berbagai bukti dan mendatangkan saksi yang kuat karena pelaku juga melakukan kekerasan verbal pada saksi (orang tua korban). Pelanggaran KDRT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Seseorang dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi dan hukuman jika terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.
Dalam kasus ini, korban hanya minta untuk cerai dan tidak melaporkan kasus kekerasannya. Namun, bukti-bukti dan pernyataan para saksi tidak dipertimbangkan secara memadai oleh hakim. Padahal, seharusnya bukti dan saksi tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai.
Hakim memaksa korban untuk melakukan mediasi berulang yang merugikan waktu, energi, dan menguras mental korban. Dalam proses sidang kedua juga dinyatakan bahwa ada mediasi yang berhasil sebagian. Namun, korban tidak pernah merasa ada mediasi yang berhasil. Justru pelaku kerap melakukan tekanan psikis pada korban selama masa mediasi dan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan.
Negara, dalam hal ini diwakili oleh hakim, tampak tidak memihak kepada korban dan melindungi pelaku. Dari kasus ini, perempuan tidak hanya menjadi korban dalam ranah personal, tetapi juga mengalami kekerasan sistemik dari negara. Padahal, ketika sudah ada bukti kekerasan sekecil apa pun, seseorang berhak untuk memperoleh keadilan. Aparat penegak hukum seharusnya memprioritaskan melindungi korban terlebih dahulu dibandingkan untuk mengejar target penekanan angka perceraian.
Memahami Siklus KDRT dan Keputusan Korban KDRT
Kasus KDRT merupakan kasus yang cukup kompleks mengingat korban dan pelaku memiliki kemelekatan yang kuat, terlebih jika usia pernikahan berlangsung cukup lama. Pada penanganan kasus KDRT, konselor atau pendamping perlu memahami siklus KDRT.
KDRT merupakan siklus yang berputar dan mengakibatkan korban berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangganya adalah kesalahannya. Hal ini karena pelaku sering kali memanipulasi korban ketika berada dalam fase bulan madu dan situasi hubungan baik. Pada kedua fase tersebut, pelaku bersikap agar korban percaya bahwa pelaku akan berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan. Kepercayaan ini menyebabkan korban akan semakin menormalisasi KDRT yang terjadi. Karena percaya pelaku akan berubah, korban “menantikan” fase-fase situasi hubungan baik dan bulan madu setelah terjadi ketegangan konflik dan kekerasan. Dengan demikian, lingkaran KDRT tidak pernah terputus dan semakin menguat.
Dalam menangani kasus KDRT atau kekerasan dalam relasi romantis, kesadaran korban merupakan suatu momen yang penting. Kesadaran ini tidak dibangun dari pemaksaan, tetapi dari refleksi yang dapat dipertimbangkan oleh korban. Pada penanganan kasus KDRT, konselor, pendamping, maupun siapa pun tidak bisa memaksakan kehendak korban dalam mengambil keputusan. Korban perlu menyadari sendiri mengenai kekerasan yang dialaminya merupakan suatu siklus. Konselor atau pendamping juga perlu memetakan risiko dan mitigasinya apabila korban memilih bercerai atau bertahan. Dalam memilih, korban harus sadar terhadap risiko-risiko yang akan dia hadapi ke depan karena yang menjalani kehidupan setelah pilihan tersebut adalah korban sendiri.
Pada konseling di ruang aman Yayasan Pribudaya, konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk transformasi kritis dan kesadaran pada korban. Hal pertama yang dilakukan adalah PFA untuk memvalidasi emosi dan perasaan korban terlebih dahulu. Sering kali korban merasa bahwa pelaku dapat berubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Dari hal ini, konselor atau pendamping yang mengawal akan lebih banyak memberikan pernyataan dan pertanyaan reflektif dan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan dalam suatu relasi. Selanjutnya, konselor mengkonfirmasi apa yang membuat korban ragu dalam mengambil keputusan dan memandu untuk memahami perbedaan KDRT dan ujian pernikahan.
Setiap langkah yang diambil oleh korban merupakan keputusan yang dilakukan secara sadar dan semua langkah yang ditempuh akan dilalui oleh korban. Konselor bertugas untuk memetakan permasalahan dan memitigasi risiko dari langkah-langkah yang akan dilalui korban. Dengan demikian, korban tidak terpaksa menerima nasihat maupun saran dari pihak luar. Dari proses ini, seseorang yang menjadi “korban” akan bertransformasi menjadi seorang “penyintas”. Validasi emosional, ruang aman, dan dukungan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan jangka panjang korban KDRT, termasuk melalui pendampingan lapangan dan grup koordinasi.
Selain pendampingan secara langsung, Yayasan Pribudaya juga telah mendampingi 23 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) selama Juni 2025 untuk dukungan psikososial melalui layanan konseling online. Layanan dukungan psikososial dan pendampingan korban secara langsung selama April-September 2025 ini didukung oleh Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Pundi Perempuan 2025 Termin I. Disclaimer: Catatan pembelajaran ini tidak memberikan informasi spesifik berupa nama korban dan pelaku, alamat tempat tinggal korban maupun pendamping korban, dan informasi spesifik lainnya yang dapat mengancam keamanan korban. Informasi lebih lengkap hanya dijelaskan dalam dokumen laporan pendampingan. Catatan pembelajaran hanya memberikan informasi terkait kasus secara singkat, kondisi korban, bentuk kekerasan, faktor yang memengaruhi kondisi korban, proses dukungan psikososial dan pendampingan korban, strategi, tantangan dan refleksi dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh tim konselor dan pendamping korban dari Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya). Layanan dukungan psikososial dan pendampingan korban secara langsung selama April-September 2025 ini didukung oleh Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Pundi Perempuan 2025 Termin I.
Seorang perempuan merasa putus asa setelah lima tahun terperangkap dalam pernikahan penuh kekerasan. Dia merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran rumah tangga oleh suaminya sendiri, yang secara berulang melakukan kekerasan fisik, verbal, dan finansial, bahkan di hadapan anak-anak mereka. Di tengah rasa takut dan kebingungan yang terus menghantui, korban akhirnya memberanikan diri mengakses platform @perempuanberkisah dari Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh dan Berdaya (Pribudaya). Korban kini telah mengajukan gugatan cerai dan mengikuti dua kali persidangan. Namun, dalam proses tersebut, ia merasa dirugikan karena pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikannya diabaikan oleh hakim. Menjelang persidangan ketiga, korban akhirnya menghubungi pos bantuan hukum (posbakum) untuk meminta pendampingan dari advokat agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil.
Apa yang Terjadi pada Korban?
Berdasarkan pernyataan korban, korban mengalami KDRT secara fisik, verbal, dan finansial selama lima tahun pernikahan, serta mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh. Lebih menyakitkan lagi, kekerasan fisik itu kerap terjadi di hadapan anak-anak mereka. Setiap kepulangan pelaku ke rumah justru memunculkan rasa takut dan cemas dalam diri korban. Pelaku sering menyalahkan korban atas segala sesuatu yang terjadi dan melakukan gaslighting agar korban merasa bersalah dan tidak berdaya. Selama menikah, korban tidak pernah didengarkan dan selalu dianggap salah.
Di tengah situasi ini, korban akhirnya mengajukan gugatan cerai pada pertengahan 2025. Namun, sebelum sidang pertama, ia diliputi rasa ragu dan cemas apakah keputusannya tepat. Korban takut dianggap kurang sabar, takut akan karma, dan merasa berat meninggalkan rumah tangganya. Pihak keluarga pelaku bahkan berusaha untuk membujuk korban untuk berubah pikiran dan berusaha agar korban menangguhkan perceraian.
Manipulasi Pelaku dan Tekanan Hakim yang Tidak Berpihak
Setelah sidang pertama, pelaku masih sering menghubungi korban, tetapi komunikasi itu tidak pernah membawa kelegaan. Sebaliknya, pelaku terus menyudutkan korban atas keputusannya menggugat cerai, menganggap langkah itu sebagai bentuk ketidaksetiaan, dan kesalahan fatal. Pelaku bahkan beberapa kali menunjukkan sikap seolah merasa bersalah, tetapi dibalut dengan manipulasi emosional.
Dalam proses persidangan, tekanan yang dialami korban semakin berat. Hakim meminta ada mediasi kembali, meskipun korban telah tegas menyatakan tidak ingin rujuk. Pernyataan korban tidak dianggap serius oleh hakim dan justru dilakukan mediasi sekali lagi. Di depan publik, pelaku tampak meyakinkan dan terlihat seperti sosok yang layak dipercaya, sehingga banyak pihak memihak padanya.
Ketika sidang kedua berlangsung, tekanan datang tidak hanya dari pelaku tetapi juga dari pihak keluarga pelaku yang berusaha mendamaikan mereka. Hal ini mengakibatkan korban menghadapi banyak tantangan dalam proses hukum. Korban merasa suaranya tidak didengarkan dan kesaksiannya diabaikan. Korban berkali-kali menyatakan bahwa ia sudah tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan, tetapi hakim tampak lebih mengedepankan “perdamaian” semu daripada mendengarkan kebenaran dari korban.
Situasi ini menambah beban psikologis yang besar bagi korban, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keberpihakan dalam proses hukum. Karena merasa dirugikan dalam proses sebelumnya, menjelang sidang ketiga, korban akhirnya mengakses pos bantuan hukum (posbakum) untuk mendapatkan pendampingan advokat dan memperkuat posisinya dalam memperjuangkan haknya sebagai korban.
Proses Pendampingan Psikososial dari Tim Perempuan Berkisah
Setelah menerima informed consent, korban diarahkan oleh admin menuju ke Ruang Aman untuk melakukan konseling secara online.
1. Sesi Pendampingan Pertama
Dalam sesi pertama, korban menyampaikan kecemasan dan kebimbangan yang ia rasakan, terutama terkait keputusan menggugat cerai. Konselor melakukan psychological first aid (PFA) dan memvalidasi perasaan korban, termasuk keraguan dan ketakutannya. Konselor menjelaskan bahwa keputusan korban untuk bercerai sudah tepat karena KDRT tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.
Konselor juga membantu korban membedakan antara ujian pernikahan dan bentuk kekerasan yang sistematis. KDRT adalah bentuk ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku berupaya menekan dan memanipulasi korban sehingga korban kehilangan daya dan selalu merasa bersalah. Sebaliknya, ujian pernikahan adalah tantangan yang dihadapi bersama secara setara, bukan bentuk penindasan.
Dalam sesi pertama ini, korban juga menyampaikan kebutuhan untuk didampingi secara langsung. Setelah dilakukan pemetaan wilayah, diketahui bahwa korban tinggal di daerah yang sama dengan salah satu anggota komunitas Perempuan Berkisah (PB). Setelah pemetaan wilayah dan kebutuhan, konselor Yayasan Pribudaya membentuk grup daring untuk koordinasi antara konselor, pendamping lapangan, dan korban sebagai dukungan berkelanjutan.
2. Sesi Pendampingan Kedua dan Ketiga
Dalam pendampingan lapangan berikutnya, pendamping bertemu langsung dengan korban untuk memastikan kesiapan emosional dan administratif menghadapi proses persidangan. Saat sidang pertama berlangsung, anggota PB turut mendampingi di Pengadilan Agama di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Meski tidak diperkenankan masuk ruang sidang, kehadiran anggota PB di luar ruang berupaya memberikan rasa aman dan dukungan emosional bagi korban. Grup koordinasi juga menjadi ruang aman tempat korban membagikan perasaannya selama menjalani proses perceraian.
Refleksi Pendampingan Korban
Negara Lemah dalam Melindungi Korban KDRT
Pada kasus ini, korban sudah mengumpulkan berbagai bukti dan mendatangkan saksi yang kuat karena pelaku juga melakukan kekerasan verbal pada saksi (orang tua korban). Pelanggaran KDRT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Seseorang dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi dan hukuman jika terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.
Dalam kasus ini, korban hanya minta untuk cerai dan tidak melaporkan kasus kekerasannya. Namun, bukti-bukti dan pernyataan para saksi tidak dipertimbangkan secara memadai oleh hakim. Padahal, seharusnya bukti dan saksi tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai.
Hakim memaksa korban untuk melakukan mediasi berulang yang merugikan waktu, energi, dan menguras mental korban. Dalam proses sidang kedua juga dinyatakan bahwa ada mediasi yang berhasil sebagian. Namun, korban tidak pernah merasa ada mediasi yang berhasil. Justru pelaku kerap melakukan tekanan psikis pada korban selama masa mediasi dan tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan.
Negara, dalam hal ini diwakili oleh hakim, tampak tidak memihak kepada korban dan melindungi pelaku. Dari kasus ini, perempuan tidak hanya menjadi korban dalam ranah personal, tetapi juga mengalami kekerasan sistemik dari negara. Padahal, ketika sudah ada bukti kekerasan sekecil apa pun, seseorang berhak untuk memperoleh keadilan. Aparat penegak hukum seharusnya memprioritaskan melindungi korban terlebih dahulu dibandingkan untuk mengejar target penekanan angka perceraian.
Memahami Siklus KDRT dan Keputusan Korban KDRT
Kasus KDRT merupakan kasus yang cukup kompleks mengingat korban dan pelaku memiliki kemelekatan yang kuat, terlebih jika usia pernikahan berlangsung cukup lama. Pada penanganan kasus KDRT, konselor atau pendamping perlu memahami siklus KDRT.
KDRT merupakan siklus yang berputar dan mengakibatkan korban berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangganya adalah kesalahannya. Hal ini karena pelaku sering kali memanipulasi korban ketika berada dalam fase bulan madu dan situasi hubungan baik. Pada kedua fase tersebut, pelaku bersikap agar korban percaya bahwa pelaku akan berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan. Kepercayaan ini menyebabkan korban akan semakin menormalisasi KDRT yang terjadi. Karena percaya pelaku akan berubah, korban “menantikan” fase-fase situasi hubungan baik dan bulan madu setelah terjadi ketegangan konflik dan kekerasan. Dengan demikian, lingkaran KDRT tidak pernah terputus dan semakin menguat.
Dalam menangani kasus KDRT atau kekerasan dalam relasi romantis, kesadaran korban merupakan suatu momen yang penting. Kesadaran ini tidak dibangun dari pemaksaan, tetapi dari refleksi yang dapat dipertimbangkan oleh korban. Pada penanganan kasus KDRT, konselor, pendamping, maupun siapa pun tidak bisa memaksakan kehendak korban dalam mengambil keputusan. Korban perlu menyadari sendiri mengenai kekerasan yang dialaminya merupakan suatu siklus. Konselor atau pendamping juga perlu memetakan risiko dan mitigasinya apabila korban memilih bercerai atau bertahan. Dalam memilih, korban harus sadar terhadap risiko-risiko yang akan dia hadapi ke depan karena yang menjalani kehidupan setelah pilihan tersebut adalah korban sendiri.
Pada konseling di ruang aman Yayasan Pribudaya, konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk transformasi kritis dan kesadaran pada korban. Hal pertama yang dilakukan adalah PFA untuk memvalidasi emosi dan perasaan korban terlebih dahulu. Sering kali korban merasa bahwa pelaku dapat berubah menjadi lebih baik di kemudian hari. Dari hal ini, konselor atau pendamping yang mengawal akan lebih banyak memberikan pernyataan dan pertanyaan reflektif dan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan dalam suatu relasi. Selanjutnya, konselor mengkonfirmasi apa yang membuat korban ragu dalam mengambil keputusan dan memandu untuk memahami perbedaan KDRT dan ujian pernikahan.
Setiap langkah yang diambil oleh korban merupakan keputusan yang dilakukan secara sadar dan semua langkah yang ditempuh akan dilalui oleh korban. Konselor bertugas untuk memetakan permasalahan dan memitigasi risiko dari langkah-langkah yang akan dilalui korban. Dengan demikian, korban tidak terpaksa menerima nasihat maupun saran dari pihak luar. Dari proses ini, seseorang yang menjadi “korban” akan bertransformasi menjadi seorang “penyintas”. Validasi emosional, ruang aman, dan dukungan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan jangka panjang korban KDRT, termasuk melalui pendampingan lapangan dan grup koordinasi.
Selain pendampingan secara langsung, Yayasan Pribudaya juga telah mendampingi 23 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) selama Juni 2025 untuk dukungan psikososial melalui layanan konseling online. Layanan dukungan psikososial dan pendampingan korban secara langsung selama April-September 2025 ini didukung oleh Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Pundi Perempuan 2025 Termin I.
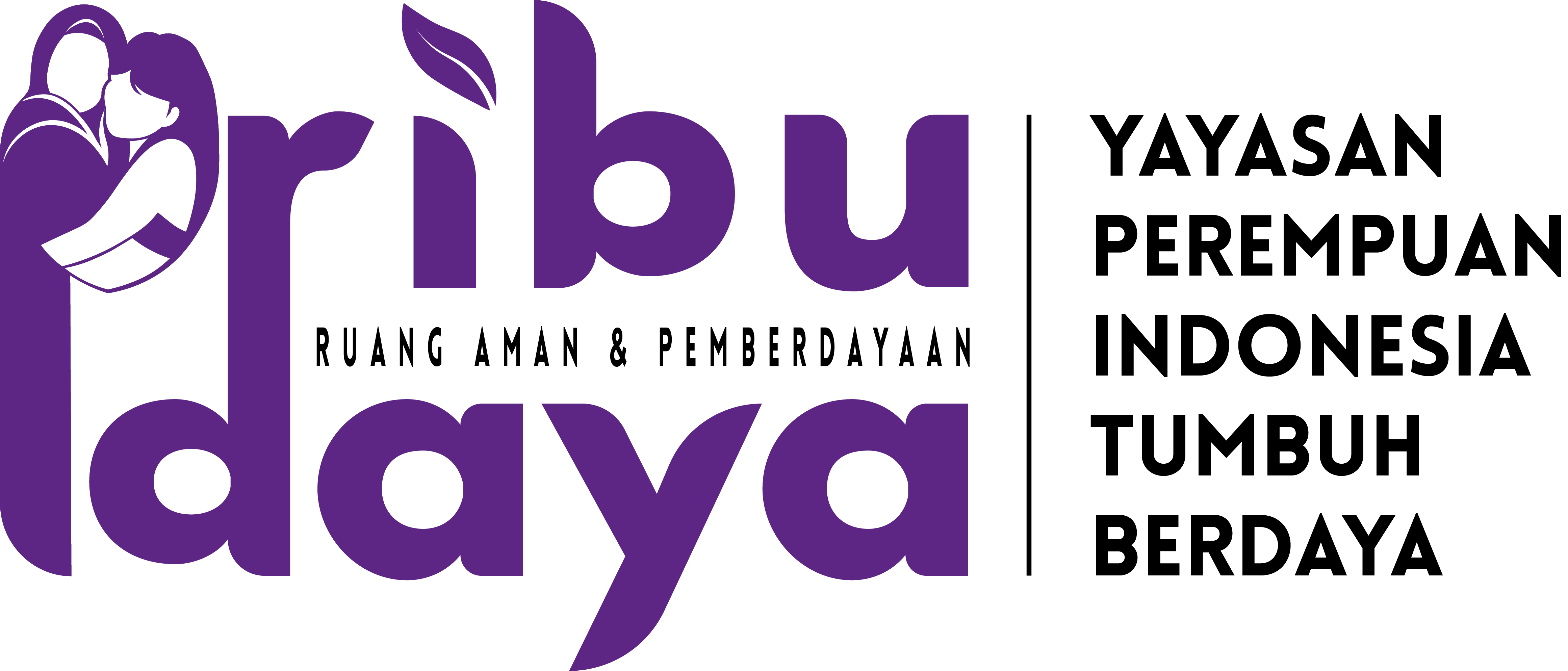


Sign up now and access top-converting affiliate offers! https://shorturl.fm/KVOHm
Join our affiliate program today and earn generous commissions! https://shorturl.fm/Szyhl
Start earning every time someone clicks—join now! https://shorturl.fm/hXd5s
Join our affiliate community and maximize your profits—sign up now! https://shorturl.fm/L3OsQ
Join our affiliate program and start earning commissions today—sign up now! https://shorturl.fm/ZEPtw
Become our affiliate—tap into unlimited earning potential! https://shorturl.fm/0VJUQ
Partner with us and enjoy recurring commission payouts! https://shorturl.fm/a6Qfb
Earn up to 40% commission per sale—join our affiliate program now! https://shorturl.fm/hnv9M
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now! https://shorturl.fm/2vG23
https://shorturl.fm/JHfY5
https://shorturl.fm/wCKeP
https://shorturl.fm/0hJwl
https://shorturl.fm/RNQdF
https://shorturl.fm/Jnqsx
https://shorturl.fm/79Jwv
https://shorturl.fm/QqXE6
https://shorturl.fm/eL1B4
https://shorturl.fm/OpYc0
https://shorturl.fm/Bxvob
https://shorturl.fm/a79sN
https://shorturl.fm/sYl4S
https://shorturl.fm/Eug1q
https://shorturl.fm/h3xkw
https://shorturl.fm/D1TQx
https://shorturl.fm/pK2t7
https://shorturl.fm/quq0V
https://shorturl.fm/Jq6Vc
https://shorturl.fm/Zt9A8
https://shorturl.fm/hL9Nj
https://shorturl.fm/76tEn
https://shorturl.fm/1CiZA
https://shorturl.fm/4Tnnb
https://shorturl.fm/s0SHr
https://shorturl.fm/Trp7I
https://shorturl.fm/l703d
https://shorturl.fm/BPDwD
https://shorturl.fm/lHQR1
https://shorturl.fm/YUAyH
https://shorturl.fm/rBT9I
https://shorturl.fm/WXtcD
https://shorturl.fm/vTECo
https://shorturl.fm/66Sc5
https://shorturl.fm/3Nw50
https://shorturl.fm/p5csn
https://shorturl.fm/e5FGm
https://shorturl.fm/HDndu
https://shorturl.fm/Lebl1
https://shorturl.fm/PS1tE
https://shorturl.fm/1Vwfy
https://shorturl.fm/zSika
https://shorturl.fm/zK8mh
https://shorturl.fm/GiFB6
https://shorturl.fm/hzA9J
https://shorturl.fm/WLPOk
https://shorturl.fm/e9wAf
https://shorturl.fm/VMosV
https://shorturl.fm/VZn4w
https://shorturl.fm/FbRz1
https://shorturl.fm/innGf
https://shorturl.fm/QHbdz
https://shorturl.fm/ROoGx
https://shorturl.fm/B4693
https://shorturl.fm/TowAA
https://shorturl.fm/kmTZ3
https://shorturl.fm/ptcFK
https://shorturl.fm/YBrZl
https://shorturl.fm/0M6wU
https://shorturl.fm/5Cm2v
https://shorturl.fm/ftQ68
https://shorturl.fm/vm3Dg
https://shorturl.fm/pI6p1
https://shorturl.fm/d6FAX
https://shorturl.fm/BKECl
https://shorturl.fm/bcVoS
https://shorturl.fm/pIL1D
https://shorturl.fm/5JJHu
https://shorturl.fm/sBO0P
https://shorturl.fm/HXBxO
https://shorturl.fm/ulKfA
https://shorturl.fm/Vj3py
https://shorturl.fm/NeT40
https://shorturl.fm/TXhCr
https://shorturl.fm/uk41C
https://shorturl.fm/d4lGS
https://shorturl.fm/KL6gM
https://shorturl.fm/HZlJG
https://shorturl.fm/70NIt
https://shorturl.fm/LIKmi
https://shorturl.fm/pUaMN
https://shorturl.fm/ZnxgB
https://shorturl.fm/y1Nch
https://shorturl.fm/lg6Ul
https://shorturl.fm/687ND
https://shorturl.fm/pNm6Y
https://shorturl.fm/T2SE2
https://shorturl.fm/OmPWA
Smart bankroll management is key, regardless of the game! Seeing platforms like bigbunny games embrace Filipino culture is a nice touch – adds to the experience, right? Always bet responsibly! 🍀
That’s a solid point about bankroll management! Seeing platforms like bigbunny apk embrace Filipino culture with modern tech is interesting-it feels more connected to the roots of the game, you know? Good read!
That’s a fascinating point about blending tradition & tech! BigBunny seems to really embrace Filipino culture – a unique approach. Thinking of checking out bigbunny slot and seeing what all the buzz is about – sounds like a fun, culturally rich experience! ✨
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.info/sv/register-person?ref=GQ1JXNRE
https://shorturl.fm/QYO2j
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
https://shorturl.fm/nZmLB
https://shorturl.fm/gA8NR
Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers. https://www.binance.com/es-MX/register?ref=GJY4VW8W
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
https://shorturl.fm/DqB3u
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.info/sl/register?ref=I3OM7SCZ
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.info/da-DK/register?ref=V3MG69RO
Thanks for addressing this topic—it’s so important.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.info/es-AR/register-person?ref=UT2YTZSU
Your passion for the topic really shines through.
https://shorturl.fm/bUYbY
I appreciate the real-life examples you added. They made it relatable.
I hadn’t considered this angle before. It’s refreshing!
https://shorturl.fm/rdKby
I appreciate the real-life examples you added. They made it relatable.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thank you for covering this so thoroughly. It helped me a lot.
What I really liked is how easy this was to follow. Even for someone who’s not super tech-savvy, it made perfect sense.
https://shorturl.fm/kbg37
You’ve sparked my interest in this topic.
I hadn’t considered this angle before. It’s refreshing!
This gave me a whole new perspective. Thanks for opening my eyes.
Earn your airdrop on Aster https://is.gd/ZceEI6
**mitolyn reviews**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Join our affiliate program and start earning today—sign up now!
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.info/zh-TC/register?ref=DCKLL1YD
Get paid for every referral—enroll in our affiliate program!
**backbiome**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.
Drive sales, earn commissions—apply now!
Earn passive income with every click—sign up today!
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your style is very unique in comparison to other folks
I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have
the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.
Start earning every time someone clicks—join now!
I’ve bookmarked this post for future reference. Thanks again!
I never thought about it that way before. Great insight!
Join our affiliate family and watch your profits soar—sign up today!
This post gave me a new perspective I hadn’t considered.
I appreciate the depth and clarity of this post.
Hello, I check your blogs daily. Your writing style is witty, keep up the good work!
I like how you presented both sides of the argument fairly.
You made some excellent points here. Well done!
I wasn’t expecting to learn so much from this post!
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.